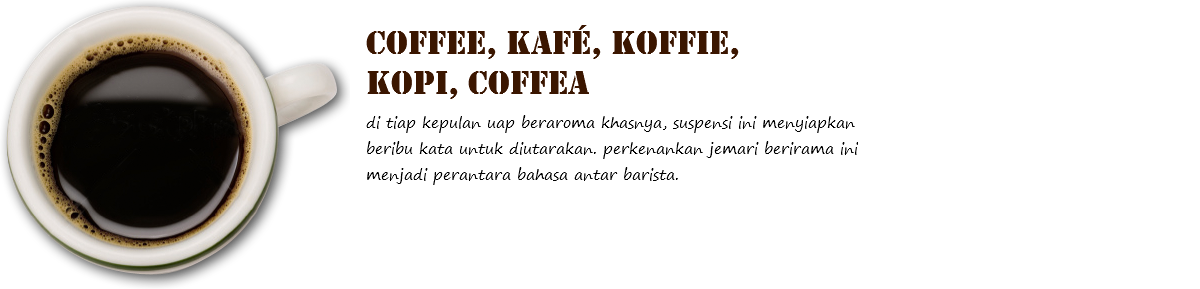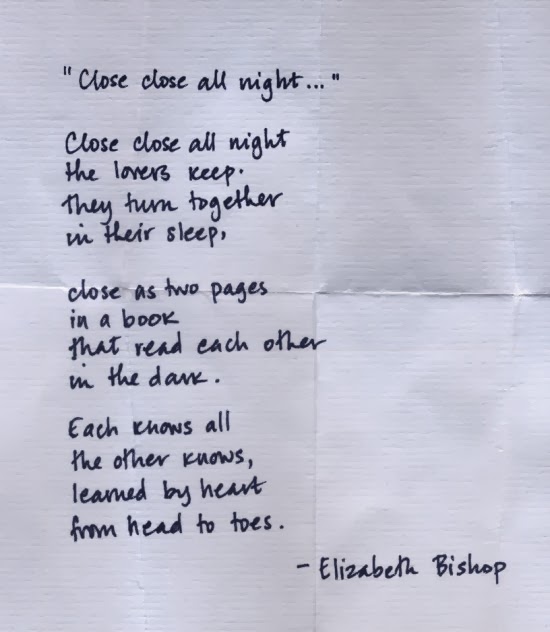Kamu
yang terdiam bersama lembaran-lembaran kertas penuh frasa dan kalimat ambigu
serba rumit. Memaku kaki di lantai keramik putih berpola sederhana yang kamu
buat retak ketika sebuah sentakan palu bertemu kepala paku yang datar, lebih datar
dari caramu membaca paragraf-paragraf yang terbit setiap harinya dari ujung
pena yang selalu hilang sebelum tintanya terkuras habis.
Kertas-kertas
berpuisi itu memintamu untuk membacanya setiap malam, sekeras suara adzan yang
rutin terdengar di mulut toa masjid di persimpangan rumahmu. Memejam menjadi
isyarat ketidakan untuk permohonan mereka. Kamu membuat puisi-puisi itu bukan
untuk dibaca segaduh teriakan anak jalanan yang dihujani klakson mobil mewah,
atau sekeras muadzin yang bersemangat di senja pertama bulan puasa. Puisimu tak
akan pernah terbaca. Kamu membuatnya hanya untuk berdiskusi dengan
retakan-retakan hati, dengan kunang-kunang yang hanya terlihat indah di
buku-buku bergambar, dengan setangkai mawar yang kelopaknya mulai berguguran
sedikit, dengan detakan jam berbentuk persegi kecil di atas meja... tentang
dia.
Dia
yang tak pernah kamu mengerti, yang sulit untuk diterka-terka seperti trik-trik
pesulap jalanan di trotoar kota Sidney.
Pada
bunyi gesekan jarum jam terkecil pertama, kamu berharap dia datang,
menyumpah-serapahi pada semua perasaan yang sebelumnya kalian puja hingga dia
muak dan berhenti mencela, menyesali semua kebodohannya untuk percaya pada
halusinasi saraf-saraf yang mengirimkan sinyal ke otaknya untuk jatuh cinta
kepadamu. Kemudian kamu berikan sekotak penuh kenangan kalian selama
berbulan-bulan setelah sore di mana kamu nyatakan perasaan dengan merah di
muka, berisi potongan tiket-tiket bioskop yang terlipat di saku celana, struk
pembelian dari berbagai minimarket di setiap sudut kota, bon pembayaran makan
siang yang biasanya menebali dompet, foto-foto yang mengajarkan dunia bagaimana
cara bercengkrama tanpa harus malu dipandang orang-orang dengan alis mata
ditarik ke atas. Seketika memerah iris matanya karena asap dari abu yang tak
habis dilalap api, karena asap dari barang-barang yang menjadi bukti kalian
pernah sama-sama tergila-gila.
Tapi,
di dentangan bunyi jarum berikutnya kamu berharap dia datang, melingkarkan
tangannya di pundakmu, mengamini semua doa-doa yang kamu bisikan seusai salam,
dan mengajak untuk sekali lagi jatuh cinta bersama, melewati batas tertinggi,
melewati batas rasa tergila-gila lebih dari orang yang pertama kali mencetuskan
istilah abstrak itu. Kemudian dia membisikan ribuan janji untuk tetap berdiam
dalam perasaan yang dibekukan agar tak mencair dan habis mengalir, sebelum
mengecup ringan bibirmu yang sudah kering, bahkan kelenjar air liurmu pun
berhenti karena senangnya.
Puisimu
hanya bisa menghiasi dinding kamar yang penuh noda kopi di sana-sini setelah
setiap malam kamu guyur dengan sisa-sisa yang harusnya jadi tegukan terakhir,
yang kamu rekatkan tiap sisinya dengan selotip bening, tapi tak setransparan
isi kepalamu tiap kali berdiri di tengah ruang tidur berantakan itu, ketika
kamu kemudian berputar-putar beberapa kali sampai menyadari kamu tak memiliki
lagi spasi kosong untuk ditempeli. Puisi terakhir yang seharusnya jadi salam
perpisahanmu sebelum benar-benar pergi.
Kamu
sampai harus menambah lingkaran hitam ekstra di sekeliling mata untuk mebuat
pernyataan perpisahan kalian, puisi yang kamu bilang sebagai tanda terlepasnya
simpul yang mengikat kata-kata takdir yang dulu sering jadi bahan obrolan
serius ataupun sekedar candaan, karena tak ada yang mampu meyakinkanmu pada
awalnya bahwa semua telah usai. Tak ada kata, peluk, cium, atau suara gema
langkah kaki yang beranjak pergi, atau sebuah ledakan amarah yang membuatmu
berubah pikiran, seperti kata ‘pergilah’ yang mungkin bisa jadi kata kunci
untuk membuatmu sekali lagi berubah jadi debu dan berhenti memperjuangkan
cinta, sebagai penanda dramatis bahwa sebuah akhir telah diputuskan bersama.
Sekarang
hanya tinggal kamu sendiri bersama selembar puisi yang bingung. Puisi yang
hanya bisa kamu pegang erat dengan kaki masih terpaku sedari tadi. Puisi
perpisahan yang hanya bisa ikut berdiri di tengah-tengah puisi kenangan. Kamu
mulai menipis, kamu jadi semakin terlihat mirip dengan kertas buram. Dengan
prosa romantis yang mengalir dalam darah dan menjeplak ke atas kulitmu, kamu
seperti puis berdiri.