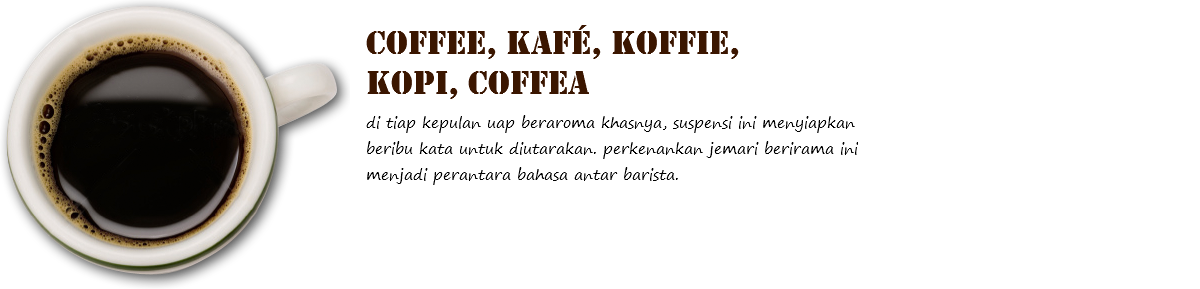13
Mei 1998
Pagi
itu aku dibangunkan oleh ketukan palu milik pegawai-pegawai Koh Wen yang sedang
bekerja. Mereka memasang papan nama yang terbuat dari kayu jati bertuliskan “Kedai Kopi: Tiga Doea” dengan dawat
berwarna merah dan lukisan naga yang tidur melingkari sebuah biji kopi. Sementara kamu sedang mengusir jauh
debu dari meja-meja yang sudah kita susun kemarin pagi. Lantai dasar yang
biasanya dipakai untuk ruang tamu dan ruang makan kita bongkar habis-habisan.
Mengangkut semua yang tidak perlu ke lantai satu, masukkan ke kamar tidur,
gudang, atau letakkan saja di balkon yang sempit itu. Dalam dua hari kerja,
ruko minimalis di pusat pecinaan yang sebelumnya hanya tempat tinggal biasa,
bertransformasi menjadi ruko minimalis
di pusat pecinaan yang akan ramai dikunjungi orang-orang setiap harinya.
Para
tetangga yang sedang menyiapkan barang dagangannya berhenti sejenak dan
menatapku yang baru saja keluar dengan penuh keheranan. Mereka sedang
menyaksikan orang cina ter-tidak-konvensional sepanjang era reformasi. Koh Liu
menghampiriku sambil membawa sekop eskrim yang belum sempat diletakkannya. Dia
mengacungkan alat pengeruk mini itu di depan wajahku dengan ekspresi merah
padam “Elu orang mau bikin kopi dari daun-daunan?! Gue emang pernah bilang sama
elu kalo semua yang elu bisa lakuin pasti punya nilai ekonomis. Tapi mana ada
orang yang mau datang ke warung kopi punya Cina! Mereka lebih percaya dengan
restoran-restoran punya orang Yahudi di Jalan Juanda sana! Karena memang itulah
keahlian mereka. Gue rasa elu orang udah kehabisan akal kali, ya!”
Aku
hanya bisa membalas perkataan Koh Liu dengan senyuman. Koh Liu yang makin
keheranan meninggalkanku bersamaan dengan para pegawai Koh Wen yang berizin
untuk pergi karena pekerjaannya sudah dituntaskan. “Kalian nggak mau nyoba
ngopi dulu? Saya kasih gratis buat kalian karena sudah bantu saya pasang papan
nama.” Tawarku sambil menggiring mereka masuk ke dalam. Keduanya tampak ragu.
Matanya sama persis dengan milik Koh Liu barusan.
“Ini,
diminum dulu kopinya mumpung masih hangat. Nanti habis ini kalian jalan ke toko
eskrim di seberang sana, ya. Tolong bilangin sama yang punya toko itu gimana
rasanya kopi buatan saya.” Keduanya menyeruput kopi itu dengan kaku. Namun,
perlahan-lahan matanya yang semula redup seolah menemukan sumber energi baru
yang membuatnya kembali menunjukkan sorot aslinya.
Keduanya
berpamit sambil mengucapkan terimakasih atas pengalaman meminum salah satu kopi
terbaik di hidupnya. Paling tidak begitulah kira-kira pujian yang diberikan
salah satu pegawai Koh Wen itu. Keduanya melangkah keluar pintu dan perlahan
menghilang dari jarak pandang normalku yang berdiri di belakang sebuah meja
kayu yang menutup sampai bawah, membuat kaki telanjangku tak terlihat oleh
pengunjung.
Batinku
tertarik untuk mengintip sedikit dari balik bingkai pintu yang terbuka lebar.
Keduanya sedang asik berdebat dengan Koh Liu. Yang satu bercerita dengan penuh
semangat sampai mengepal-ngepalkan tangan di udara. Sementara partnernya sibuk
menjilati eskrim sambil mengacung-ngacungkan dua jari, bersumpah atas nama Dewa
Eskrim bahwa apa yang diceritakan temannya terbebas dari unsur kebohongan. Kopi
di pagi hari memang nikmat, tapi tak senikmat menghirup aroma kepuasan melihat
Koh Liu berjalan cepat kearah kedaiku, dengan ekspresi ingin tahu yang membara.
Segera kubenarkan apron kulit yang sudah agak longgar sambil bergegas ke
belakang stasiun kerja, bersiap untuk sebuah pesanan plus ledakan emosi tak
percaya. Kutahan tubuhku di meja panjang yang di atasnya berjejer rapi toples
kecil berisi biji-biji kopi dan sebuah mesin pembuat kopi manual asli Belanda.
Semua proses terjadi di satu meja panjang ini: memilih biji kopi, gula, krimer,
atau hanya gula, atau gaya penyajian asal luar negeri yang mengundang tanya,
dan membayar pesanan.
“Gue
belum percaya kalo nggak cobain sendiri. Mungkin selera mereka aja yang terlalu
rendah soal kopi. Gue walaupun gak suka minum kopi tapi tahu mana yang kelas
restoran bintang lima mana kelas ibu-ibu baru nonton acara Rudy Choirudin
sekali.” Koh Liu tau-tau sudah berada di hadapanku sambil memegang mug
stainless. Ukurannya jauh lebih besar dari gelas atau cangkir yang kugunakan
untuk menyajikan pesanan. Dasar penolak rugi.
“
Siap, Koh. Nanti saya anterin ke depan kalo misalnya lagi banyak kerjaan.”
“Ah,
elu orang tau aja kalo gue lagi sibuk. Jangan manis-manis, ya. Nanti istri gue
marah. Gula gue udah mulai naik lagi.” Sambil mengelus-elus perutnya yang agak
buncit, Koh Liu beranjak keluar. Meninggalkanku sendiri bersama mug anti rugi
miliknya.
Setelah
sebuah bunyi biji kopi tergiling, dan gemericik air seduhan yang merosot turun
kedalam mug Koh Liu, segera kuantarkan pesanannya. Kedai eskrimnya sedang padat
ramai. Pengunjung keluar masuk secara bergantian. “Koh, saya taroh di atas
meja, ya!” Teriakku kepadanya yang sedang sibuk di belakang. Baru saja ingin
menuntaskan niat untuk berbalik badan kembali ke tumpukan kafein, tiba-tiba
seorang pelanggan tanpa sengaja menyenggol jatuh mug yang baru saja kuletakkan.
Tak masalah jika terjun bebas ke lantai. Yang jadi masalah ternyata terjunnya
tak bebas, tapi terhambur abstrak di dalam sekotak eskrim siap antar yang belum
ditutup kemasannya. Berbarengan dengan itu, Koh Liu keluar dan segera
mengidentifikasi masalah yang terjadi. Namun ia kalah cepat dengan kurir
pemasoknya yang dengan segera menutup kotak kemasan itu setelah mengeluarkan
mug di dalamnya tanpa dosa. Aku yang hanya bisa diam terpaku melihat Koh Liu
setengah berlari mengejar pekerjanya yang mungkin sedang mabuk polusi.
“AMSYONG!!
AMSYONG GUE!!!” Teriak Koh Liu berulang. Makin lama makin meredam. Setelah
benar-benar hening dari teriakannya, Koh Liu kembali masuk ke dalam sambil
memijat-mijat dahinya. Semua orang yang sedang menyaksikan kejadian barusan
jelas tahu, Koh Liu bukan sedang sakit kepala. Dengan enggan aku berpamit
pulang kepadanya. Jelas merasa bersalah, tapi harus diapakan lagi? Mungkin
dalam benaknya sudah tergambar sebuah penolakan besar atas maha karyanya,
dengan tuntutan pengembalian uang penuh tentunya.
Setengah
hari berlalu, masih terpikirkan nasib Koh Liu dan pesanannya yang tak sengaja
tercampur kopi. Entah apa komentar yang keluar dari pemesannya saat ini.
Maki-makian jenis apa yang sedang mereka lontarkan. Lamunanku siang itu
dipenuhi kebun binatang dan kotoran-kotoran berbagai jenis makhluk hidup.
“Kok
melamun? Nanti pelanggannya pada pergi, lho.” Suara renyah yang berasal dari
dapur itu jelas sekali milik siapa. Memang bukan obat merah, tapi kelembutannya
bisa menghentikan kebocoran darah.
“Eh?
Mbak kasirnya kok jam segini baru datang?” Kubalas candaanmu yang sedang
menyeka keringat di dahi. Terlihat letih namun tetap menegarkan diri karena
pekerjaan rumah yang biasa kita bagi sekarang menjadi tanggunganmu sendiri.
Terusan cokelat muda selutut dan cardigan
putih yang ditarik sebatas siku menjadi seragam kerjamu hari ini.
“Baru
datang apanya, kalo aku turun ke bawahnya dari tadi terus nanti siang kita mau
makan apa?”
“Nih,
biji kopi setoples. Kalo belum kenyang temennya masih sekarung di belakang.”
“Nggak
mau, ah. Bikin masuk angin. Oh, iya, nanti malam kamu di suruh Koh Liu ke
tempat dia. Tadi dia nitip pesan pas aku mau buang sampah.”
Waduh!
Mampus! Pikiranku langsung melayang kemana-mana. Membuat fantasi sesosok Koh
Liu sedang menamparku sekuat tenaga hingga terkapar. Katamu Koh Liu pernah
bercerita soal pengalamannya belajar Wushu
di kaki gunung. Semenjak tahu soal itu, aku selalu berhati-hati agar tak
mencari perkara dengannya. Pagi ini, justru pelanggannya yang tak berhati-hati
yang membawa masalah untukku.
Malam
harinya aku membawakan teko berisi kopi panas ke kedai Koh Liu. Sekedar
basa-basi agar undangannya tak terlihat sebagai alasan tunggal aku ke sana. Dia
sudah menunggu sejak matahari terbenam tadi. Duduk di meja bundar yang letaknya
di luar atap kedai, subtitusi atapnya hanya sebuah payung besar yang tertancap
di tengah-tengah meja. Dengan kaos berlambang partai politik dan celana pendek
sepahanya, Koh Liu duduk bak kaisar yang sedang menunggu prajuritnya
menyampaikan kabar perang.
“Ha!
Akhirnya elu orang datang juga. Sini duduk, ada yang mau gue omongin sama elu.
Itu kopi baunya udah sampe sini duluan, gak sabar gue mau cicip langsung.”
“Anu,
Koh, soal yang tadi pagi itu, saya mau minta maaf. Biar saya ganti berapa
ruginya tadi, Koh.”
“Rugi
gundulmu?! Gue justru dapat borongan pesanan gara-gara elu punya kopi gak
sengaja kecampur sama eskrim tadi. Mereka bilang rasanya unik. Eskrim tapi
kayak kopi, kopi tapi kayak eskrim. Gue mau minta tolong sama elu, besok pagi
gue pesan dagangan elu itu satu teko ini lagi, ya!” kalimatnya yang bercampur
tawa membuatku keheranan cukup lama. Ekspresi Koh Liu yang bercerita panjang
lebar dengan senyum yang tak kalah lebar berbanding terbalik dengan matanya
yang menyipit dan nyaris hilang ketika tertawa terbahak-bahak. Malam itu, aku
mabuk rupiah mendapati bayaran tunai dari Koh Liu untuk pesanannya besok pagi.
Kembali
ke ranjang dengan berita gembira memang menyenangkan. Melihatmu tertawa dan
tersenyum seperti saat di pasar dini hari saat itu menjadi pengobat ampuh rasa
letih selepas melayani puluhan orang yang membeludak saat jam makan siang tadi,
berangsur sepi ketika sore hari, dan melonjak lagi menjelang pukul sembilan.
Hari pertama kedai ini dibuka, tak sedikit yang langsung terpikat dengan
pesonanya.
BRAAKKK!!!!
Lantang
dan menantang, seseorang membuka paksa pintu kedai di bawah. Kamu yang setengah
tidur terlonjak kaget, meremas lengan bajuku penuh cemas. “Jangan kemana-mana.
Tunggu di sini, aku mau lihat ke bawah sebentar.” Berbekal sebuah senter dan
pisau dapur bergagang longgar, aku menuruni tangga yang mungkin juga ikut
bergoyang, merambat dari getaran kakiku yang tak bisa diam.
Suara
gaduh terdengar dari bagian depan kedai. Tiga orang dengan siluet tersapu
cahaya seneter sedang mengobrak-abrik susunan meja dan lemari-lemari. Di
belakang mereka, menggeliat bayangan gelap yang menyelimuti akal sehatnya.
Sayup-sayup dari kejauhan aku mendengar suara teriakan Koh Liu dan istrinya. Di
ikuti tangisan berdarah milik Nyonya Lie, kemudian rintihan memohon ampun dari
pegawai-pegawai warung song mie duapuluh
empat jam miliknya. Hal yang berikutnya terlintas di kepalaku adalah mungkin
saat ini giliran untuk suaraku yang menggema.
Seorang
pria berkulit hitam yang membawa golok menggulingkan semua meja dan membelah
kursi-kursi yang ada menjadi berkeping-keping. Dua orang pria yang berbadan
besar berlari ke arahku yang sedari tadi memperhatikan kebrutalan mereka. Entah
kenapa yang aku pikirkan bukanlah kedai yang menjadi mimpi usahaku, atau bahkan
keselamatanku sekalipun.
“MARTHAAA!!!!”
Teriakanku bersimbah
darah segar. Volumenya perlahan-lahan menghilang tertutup cairan merah menyala.
Mataku terasa berat, sangat berat. Seolah sedang mengalami narkolepsi. Si Hitam
berjalan ke arahku dengan sepatu berujung baja khas Tentara Indonesia yang
dapat dengan mudah aku kenali karena aku pernah memakainya pula. Dengan sekali
ayunan, pelat baja di hidung sepatunya itu bertumbukkan dengan dahiku. Seketika
itu aku merasakan rasa sakit dari arah yang lain. Dibarengi dengan bayangan sebuah
tangan yang tebal dan besar terayun ke arahku.
Semuanya mendadak
berputar. Berporos pada kepalan sekeras besi yang masih diayun-ayunkan
pemiliknya ke sekujur tubuhku. Panas yang sedari tadi menggeluti lebam-lebam
yang entah berapa jumlahnya mendadak menghilang. Berganti dingin yang tak
kunjung padam. Semakin dingin ketika daging yang melekat di tulangku dilubangi
secara paksa oleh logam mungil yang dimuntahkan revolver milik salah seorang
dari mereka. Aku memejam tanpa daya. Berharap mereka menganggap aku tak lagi
bernyawa.
Pandangan
redupku menangkap ayunan kaki mereka yang menjejak tangga menuju ke lantai
atas, sementara derap langkahnya tak dapat lagi kudengar. Hanya dengingan
panjang yang menemani usahaku untuk menggerakan ujung jari. Mencoba meraih
pisau dapur yang tertancap sempurna ke lantai. Ada rasa frustasi yang
menghinggap ketika seluruh tubuhmu tak mendengarkan lagi koordinasi dari otak.
Semua menolak untuk diajak bekerja sama. Sampai sebuah lengkingan panjang
memacu adrenalinku untuk melupakan semua luka yang sedari tadi menganga.
Tubuhku
terasa seperti bulu angsa yang tak bisa melawan ketika ditiup angin, ringan,
sangat ringan, terlalu ringan. Kunaiki tangga dengan jejak lumpur yang
ditinggalkan mereka. Nyaris seperti mendaki udara karena ringannya tak terasa
lagi kaki menapak di lantai. Pandanganku menyapu seluruh ruangan di lantai
satu. Dua dari mereka entah bagaimana caranya tahu-tahu sudah berada di
bangunan sebelah, melompat dari jendela atau meniti pinggiran jeruji balkon
bisa jadi opsi yang masuk akal. Meninggalkan seorang temannya yang mendobrak
lepas pintu kamarku, diiringi dengan jeritan keduamu. Kaki-kaki yang seolah
ditarik gaya asing untuk tak bergerak kupaksakan melangkah walau membuatku
merintih tiap gerakan sendinya. Aku hanya bisa terdiam di mulut kamar ketika Si
Hitam sudah berdiri di atas ranjang dengan tangan kanan menahan mulutmu untuk
bungkam dibalik sebuah bantal. Piyama putih itu menggelepar kehilangan jatah
oksigen primernya. Ketika sudah terkulai lemas, dengan sebuah ayunan kencang Si
Hitam mengadu goloknya, membelah bantal
dan sesuatu di bawahnya menjadi dua bagian sama rata. Persis ketika kamu
membelah dua semangka yang kamu beli di pasar dini hari. Bedanya, pisau buah
berganti golok berdarah, semangka bundar berganti kepala dengan nyawa yang
memudar.
Ada
semacam heroin yang melepaskan kekanganku dari rantai-rantai rasa sakit.
Memberikan sebuah ledakan untuk menerkam Si Hitam dari punggungnya.
Menggulingkannya ke bawah dalam sekali banting. Detik berikutnya yang aku tahu,
aku sudah berada di samping ranjang, di atas Si Hitam yang pakaiannya setengah
terbuka. Matanya yang tadi membuat nyaliku ciut kini justru terpejam mengkerut.
Mungkin aku sedang berhalusinasi, pisau yang tadi menancap di lantai, sekarang
menancap di hati, goloknya yang tadi digenggam erat di tangan kiri, sekarang
digigit kuat merobek pipi.
Ketika
adrenalin berangsur habis, kembali kurasa berondongan luka meminta
diperhatikan. Seperti dikerubungi satu koloni semut api yang disiram minyak
tanah, seluruh tubuh seolah digigiti hingga ke tulang, merambat sampai organ
dalam. Cahaya terakhir yang kutangkap sebelum menggelap hanya senyummu yang
memudar, sebagian tertutup bantal putih bercorak merah.