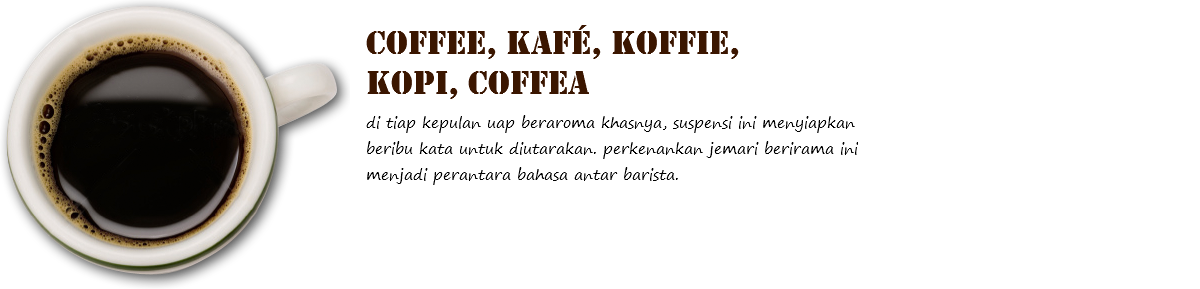Dua
cangkir porselen murah yang sudah menguning; salah satunya digenangi sisa kopi
hitam yang tadi pagi mengepulkan asap putih. Pasangannya dituangi air putih hangat
dan dua siung bawang putih. Keduanya memiliki tujuan yang berseberangan ketika
diramu dan diseduh, namun kini mereka tak bisa dipisahkan ketika aku yang
berperan sebagai penyesap. Cangkir pertama untuk memenuhi kebutuhan kafein
harian, cangkir kedua sebagai pencegah darah tinggi paling ekonomis dan
praktis. Butuh setidaknya satu piringan hitam Dean Martin untuk beralih dari
cangkir pertama ke cangkir kedua. Tidak ingin cepat-cepat kuhilangkan asam yang
menggelitik lidah. Pahitnya selalu menjadi mesin penjelajah waktu yang
mengantarkan kembali sampai ke tempat tujuan—di kursi ini, hari ini, 1998.
Tak
banyak yang hilang pada hari rabu merah limabelas tahun silam. Hanya beberapa
perabot dan pintu, sedikit daging dan otot bahu—yang sekarang sudah tumbuh
kembali, dan kamu—yang tidak bisa tumbuh kembali. Walaupun lubang bekas
tembakan liar sebesar gundu itu sudah tidak nyeri lagi, rasanya ada
lubang-lubang lain yang masih tetap menganga dan tak pernah kering lukanya.
Beberapa kali kucoba menutupnya tetapi kemudian lubang itu muncul di tempat
berbeda, menegaskan bahwa aku menyerahkan sebagian hidupku kepadamu dan telah
kehilangannya. Tak perduli berapa banyak kesepian yang coba kuredam, selalu ada
celah bagi kepergianmu untuk membuatku merasa sendirian.
Setelah
mencuci cangkir dan mengibas-ngibaskan kemoceng pada lemari-lemari dan perabot
secara sekilas kuputuskan untuk menunda dulu sarapan pagi, mengambil sepatu
olahraga, memakai kaos I love Jogja
yang kebesaran, dan mengganti sarung dengan
celana tenis—yang belum pernah masuk ke lapangan tenis seumur hidupnya.
Sekarang pukul enam tepat dan kedai baru akan melayani pesanan setengah jam
lagi. Para early bird yang singgah di
sini sebelum memulai kehidupan berasal dari dunia yang beragam; mulai dari
pejabat muda yang memesan “kopi manis” dan sarapan kecil, bapak-bapak atlet
catur, mahyong, kartu remi, dan permainan lain yang tidak membuat pantat
beranjak dari tempatnya, pekerja-pekerja malam yang belum siap pulang ke rumah,
sampai pegawai Koh Liu yang mencuri-curi waktu sebelum disibukkan pelanggan
pagi hari. Kuturuni tangga menuju lantai dasar sambil memilih-milih teman untuk
berjalan nanti. Pink Floyd? Masih
terlalu pagi. Ramones? Jack Johnson? Phil Collins? Bisa-bisa jam sepuluh baru sampai rumah lagi. Frank Sinatra? Already have too much rat pack this
morning. The Beatles? Hmm.. Who can’t
say no to Beatles?
Kunaikan rolling door dan menyapa Koh Liu yang sedang didoakan anaknya dari
lantai satu toko eskrim peninggalannya. Bau dupa yang menyelinap dari celah
jendela selalu menegurku seperti yang
dilakukan Koh Liu setiap pagi. Lima tahun lalu terakhir kali kuhidupan dupa
untukmu, setelahnya aku mulai berhenti memkirkan soal dunia setelah kehidupan
dan berpegang pada konsep bahwa energi itu bersifat kekal. Mungkin energimu
sekarang sudah berubah bentuk menjadi sesuatu yang berbeda—mungkin juga
bereinkarnasi menjadi roti bakar keju coklat—dan memberikan aroma terapi yang
menyengat tidak akan merubah keadaan sedikitpun. Setelah puas bertegur sapa
dengan abu kremasi Koh Liu dari kejauhan, aku mengambil beberapa koran harian
yang diselipkan di kotak surat dan masuk ke dalam untuk menumpuknya ke rak
majalah di sebelah meja kasir. Ketika kembali keluar seorang perempuan bergaya
kantoran menyapa dengan senyum yang tidak dibuat-buat.
“Maaf, apa sekarang sudah buka?” dia
bertanya sambil menyatukan kembali beberapa helai rambutnya yang jatuh menutupi
mata ke sela telinga dengan tangan kiri. Tangan kanannya mengapit sebuah tas jinjing
dari kertas berwarna putih. Dia datang dengan berjalan kaki sepagi ini, kurasa
tidak ada salahnya membuka kedai sedikit lebih awal agar dia bisa
mengistirahatkan mata merahnya yang berkantung.
“Ya
tentu saja, tapi saya belum menurunkan kursi-kursinya jika anda tidak
keberatan.”
Dia
berjalan masuk mengikutiku yang menurunkan sebuah kursi di depan meja bar
sambil berputar beberapa kali untuk melihat seisi ruangan. “Rasanya seperti
sedang berada di rumah ibu saya; tua dan nyaman. Apa anda bekerja sendiri?”
“Saya
dulu bekerja di sini. Sekarang saya hanya sebagai pemilik yang kadang-kadang
menyapa pelanggan dengan ramah atau mendengarkan keluhan tentang jam tutup yang
terlalu cepat. Pegawai saya baru akan datang sepuluh menit lagi.”
“Apa
itu artinya saya belum bisa memesan apa-apa sampai sepuluh menit ke depan?”
pertanyaannya diakhiri dengan menguap yang terlalu pendek untuk jam enam pagi.
Aku
berjalan ke belakang meja dan mengambil apron kulit yang tergantung di dinding.
“Artinya anda akan menyuruh pemilik kedai yang sudah kaku dan lama tidak
melayani pelanggan ini untuk melakukan pekerjaan lamanya. Silahkan pilih
pesanan anda, saya sarankan untuk tidak memesan apapun selain yang ada di
barisan pertama. Jangan rusak pagi anda dengan memesan sesuatu yang saya
sendiri tidak bisa menjamin rasanya.”
Matanya
memindai daftar menu yang tergantung di dinding yang ku belakangi. Barisan
pertama berisi berbagai cara penyajian kopi, barisan kedua minuman tanpa
kafein, barisan ketiga dan keempat berjajar daftar makanan yang ditambahkan
oleh para pegawai pada rapat pembuatan daftar menu tahun lalu. Setelah membaca
berulang sambil mengusap dagunya dia menaggalkan blazer yang menyembunyikan
kemeja putih dengan pola pinguin kecil dan berkata “Kalau begitu saya pesan Macchiato. Latte.”
“Macchiato.. Latte..” otakku memproses
semuanya dengan sekejap. Dalam satuan mach lemari-lemari pengetahuan di dalam
otakku terjelajahi. Mengurut kata kunci dan membaca cepat apa yang harus
dikirimkan melalui saraf-saraf ke seluruh tubuh; kaki bergerak ke kiri, tangan kanan
meraup segenggam biji robusta, tangan kiri menggaruk-garuk kepala karena lupa
letak gelas takar. Semuanya bekerja secara berirama, walaupun sering ditemui
nada-nada sumbang ketika ini terjatuh, itu terlalu banyak, dan di mana letaknya
anu.
Helaan
nafas panjang berkali terdengar nyaring namun tanganku tak kunjung berhenti
bergetar. Lama tak membuat apapun selain kopi hitam pahit membuat lagakku
seperti pegawai magang yang dipelototi bos dan pemesan pertamanya. Espresso ku tuang perlahan agar tak tercampur
dengan susu, dulu seperti menuang air putih, sekarang seperti menakar obat
maag. Pengunjung banyak yang memesan Macchiato
karena tergoda dengan lapisan-lapisan yang telihat tegas garis kontrasnya, dari
putih lembut susu perlahan menjadi keruh digoda kopi. Salah satu model yang tak
pernah luput dari sesi foto pra-drinking
menurut pengamatanku.
Belum
selesai ku tabur kayu manis di atasnya, justru senyum manis wanita tadi yang
menghabur terlebih dahulu. Dia beranjak dan menanggalkan ponsel berlayar dua
warna sambil menunjuk toko di seberang jalan mengisyaratkan tujuannya.
Langkahnya menuju lurus ke pintu keluar, namun pandangannya meratap ke atas,
seolah berharap tuhan turun dari langit-langit dan memberinya sekerucut eskrim.
Tarikan pintunya berbarengan Mbop yang hari ini datang sedikit terlambat. Mereka
berpapasan dan saling melempar teguran yang dikemas senyum penuh keseganan.
Kuserahkan
apron dan urusan kedai kepada Mbop yang sejak melangkah masuk terus meminta
maaf karena terlambat lima menit. Katanya dia harus berhenti beberapa kali
karena rantai sepedanya selalu terlepas setiap beberapa kayuhan. Mbop biasanya
mengisi presensi paling awal setiap pagi dengan harapan mendapat tambahan jam
istirahat agar bisa bercengkrama bersama super
cub warisan Koh Liu yang sampai saat ini masih kuragukan dapat hidup
kembali. Setiap siang dia akan pergi ke garasi di belakang toko eskrim seberang
jalan dan memulai operasi bedah motor selama satu jam. Kemudian dia akan
kembali ke kedai dengan tangan penuh oli hitam dan ekspresi wajah dokter bedah
yang gagal menyelamatkan pasiennya. Suatu siang aku menanyakan alasan kenapa
dia ingin menghidupkan motor tua itu lagi. Dia berkata dengan senyum yang lebar
sampai-sampai mata besarnya tinggal segaris “You meet the nicest people on a Honda.” Pada detik itu aku sadar,
dia lebih dari seorang mantan tattoo artist lulusan STM yang membaca The Design of Everyday Things sebelum
tidur.
Setelah
serangkaian ritual permintaan maafnya—mulai dari pijatan di pundak sampai
selembar permen karet rasa mint—Mbop mulai disibukkan dengan beberapa pelanggan
kepagian. Pagi ini kedai seharusnya dijalankan oleh Mbop dan dua pegawai lain
yang masih belum datang. Kakak-beradik yang terlihat anggun namun sudah biasa
bekerja keras untuk meringankan beban keluarga. Tak lama keduanya datang dan
saling melempar candaan dengan Mbop, aku memilih untuk menemani wanita tadi
yang tidak bergeming sedikitpun semejak kembali dari membeli eskrim di
seberang.
“Boleh
saya bergabung?”
“free country, of
course.” Dia memutar sedikit posisi duduknya menghadapku
kemudian menyesap ringan melalui bibir gelasnya “Rasanya seperti tenggelam ke
dalam palung laut. Perlahan-lahan cahaya mulai menyerah dan meninggalkan kita
bersama sisa-sisanya dan gelap yang senyap.” Matanya memejam tanpa paksaan,
diikuti tarikan nafas panjang yang dihabiskan utnuk satu kalimat. Tidak ada
yang lebih mengerikan selain mati tenggelam di tengah samudera. Tentu saja yang
barusan hanya kiasan, mana mungkin kopi buatanku rasanya seburuk itu sampai dia
merasa sekarat. Mungkin dia sedang membicarakan hidupnya.
Lipstik
merahnya sedikit memudar bercampur dengan kopi yang mendadak menjadi kebanyakan
gula. Tangannya kembali menyampingkan beberapa helai rambut yang terpisah dari
temannya. Mbop menginterupsi keheningan sesaat itu dengan menawariku permen
jahe yang disediakan untuk para langganan yang sering mengobrol di meja bar
hingga tenggorokan terasa serat. Kuambil satu dan mencecapnya dalam-dalam. “Tidak
terlalu buruk juga. Setidaknya sebelum mati atau keburu jadi makanan ikan
duluan, kita masih bisa menikmati keheningan sambil merasakan dinginnya didekap
samudera dalam-dalam. Pelukan mana lagi yang bisa sesejuk itu.”
“Ada
satu pelukan yang sangat dingin, mengalahkan kesejukan samudera yang acuh pada
kehadiran kita di perutnya. Aku pernah merasakannya sekali, sekali saja. Dinginnya
menjalar dari tangan yang melingkar di lengan sampai bahuku, menyelinap di sela
lapisan kulit, mengoyak-ngoyak jaringan otot, mendobrak paksa susunan tulang,
dan merengsek masuk ke dalam jantungku.” Dongengnya ia beri jeda dengan sebuah
hisapan Macchiato yang dalam. Dia habiskan
sisanya dalam satu sesi yang bisa membuat otak terasa beku. Tapi sepertiya dia
menikmati angin kutub yang berlalu sesaat di kepalanya. Mungkin dia sedang
membutuhkan referensi rasa dingin yang barang kali telah terlupakan.
Pandangannya
terjurus pada sesuatu di belakangku—atau mungkin di dahiku, atau bahkan di
dalam diriku. Ku tahu pasti yang jelas itu bukan Mbop yang sedang berkaraoke
pribadi dengan walkman-nya. Matanya meruncing
seolah menemukan jawaban yang ditulis dengan huruf yang sangat kecil. Dia berdiri
dan sedikit menjauh dari orbitku yang tak mengantisipasi akan kepergiannya yang
mendadak. Blazernya kembali terkancing rapi, barang-barangnya berbaris siap
diangkut kapanpun induknya berkomando. Tanpa salam penutup atau kalimat sampai
jumpa seperti pada surat yang biasa dibuat saat sekolah dasar, ia meraih tasnya
dan berjalan mundur perlahan, kemudian berbalik badan. Seolah kepergiannya
adalah sesuatu yang dia ingini namun masih enggan jika terealisiasi. Langkahnya
terasa berat dan kecil, semakin mendekati pintu keluar semakin tak mau
dikompromi salvatore ferragamo hitamnya
yang seolah bertambah berat.
“Sesuatu
terasa salah?” kucoba menahan perginya. Entah itu pertanyaan atau pernyataan
yang aku sendiri tak yakin. Dia berbalik dan berjalan mendekatiku. Cukup dekat
untuk membisikkan sepatah kata langsung di telinga kiriku yang menghening
seketika. Aku bisa merasakan senyumannya tanpa perlu menoleh. Dia memutar
kembali badannya dan melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Tubuhku
menolak untuk menahannya pergi sekali lagi. Rasanya sudah cukup hari ini aku
bertemu dengannya. Aku kembali ke meja bar dan mendapati secarik kertas yang
sepertinya disobek dari sebuah buku catatan tanpa paksaan. Dengan tinta
biru, tulisan yang agak miring itu mengundangku untuk kembali duduk dan
mengangkat sedikit gelas yang menghimpitnya.
“Tamam Shud.”